Jadi gini, saat aku seumuran Tian, aku emang ada niatan buat jadi guru relawan lewat Indonesia Mengajar. Kebetulan saat itu aku udah lulus D3 dan ada ketertarikan sama pendidikan anak karena selama kuliah suka ikutan ngajar anak jalanan. Tapi aku ditolak karena yang dibutuhan itu lulusan S1 dan aku juga ada kontrak kerja dua tahun.
Tiga tahun kemudian, saat aku lagi ngadepin ujian akhir kelulusan S1, Indonesia Mengajar buka rekruitmen lagi. Aku nyoba daftar, tapi ditolak karena ya aku belum punya ijazah dan dianggap belum lulus.
Setahun berlalu, saat pendaftaran ada lagi, aku udah ‘kejebak’ sama dunia dewasa dan jam kerja. Tuntutan buat segera dapet kerjaan yang tetap dan menghasilkan udah ada. Aku pun harus say goodbye sama mimpi mengajar di pelosok. Kalaupun sekarang aku nekat nyari lowongan, batas usianya udah kelewat, hehe.
Jadi kebayang dong ya apa yang aku pikirin tiap lihat adegan Torfun kayak gini, hehe.
Mengajar anak-anak di pedalaman emang seindah montase di episode satu ini. Saat aku baca buku yang ditulis mantan guru relawan Indonesia Mengajar di daerah Maluku, gak semua isinya senang-senang. Malah sebaliknya, dia struggle banget di sana. Apalagi waktu kontrak di Indonesia mengajar itu satu tahun, jauh lebih lama dibandingin yang digambarin di ATOTS yang waktu kontraknya cuma tiga bulan.
Tapi yang aku suka di ATOTS, meskipun ini soal kisah cinta, mereka gak meromantisasi ‘kemiskinan’ dan ketertinggalan masyarakat. Gak tahu ya, senangkepnya aku sih gitu. Meskipun kita dimanjain banget dengan pemandangan desa yang indah, aku gak dapat kesan kalau series ini ngasih gambaran soal kekurangan fasilitas dan akses ke dunia luar itu sebagai hal yang wajar dan ‘romantis’. Gimanapun hal itu tetep masalah dan gak bisa jadi wajar hanya karena semua warganya bahagia. Kesan ini, aku temuin dari beberapa dialog, misalnya dialog di episode 3 antara Rang sama Tian ini:
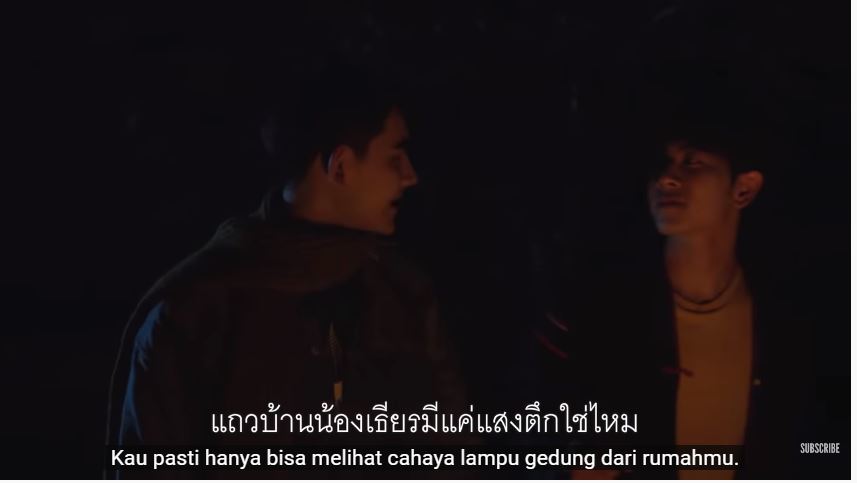
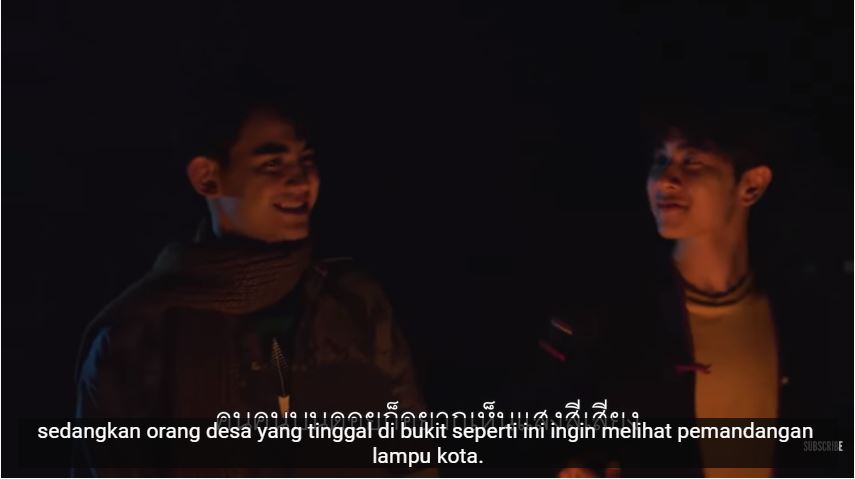
Aku suka dialog di sini, karena tokoh Rang (salah satu polisi hutan di dea) mengakhiri dialog dengan rumput tetangga memang selalu lebih hijau, saat Tian cerita dia di rumah udah jarang lihat bulan karena cahanya kehalang lampu gedung-gedung. Rang gak meromantisasi keadaan warga desa yang selama ini bisa lihat bulan dengan lebih terang, dan milih buat ngebandingin kalau mereka juga sebenernya pengen lihat lampu di perkotaan.
Terus adegan dengan editing juara yang paling aku suka di episode 4, antara Tul sama Tian ini:



Aku akui adegan ini emang bisa jadi bahasan yang panjang karena dialog dan editingnya, tapi sebelum masuk ke inti, aku udah tergelitik duluan sama dialog awal mereka berdua. Waktu itu Tul (sohib Tian dari kota) tanya kenapa Tian betah di desa tanpa listrik, internet sama ponsel, lalu Tian jawab, Kenapa enggak? Karena di sana warganya juga betah dan seneng-seneng aja, lalu Tul ngucapin kalimat di atas. Beuh! Rasanya pengen salim sama Tul.
Karena kalau gak kayak gitu, apa bedanya ATOTS sama FTV-FTV yang biasa tayang soal gadis-gadis kota yang kepaksa tinggal di desa lalu berubah betah setelah jatuh cinta di sana? (uhuk FTV setting kebun teh di puncak uhuk). Walaupun, oke, memang dialog ini kemudian menggiring pada Tian yang menceritakan soal Phupa, tapi itu gak ngeubah jika ATOTS tetap menganggap keadaan desa itu gak nyaman. Karena yang membuat Tian betah itu bukan keadaan desanya, melainkan karena di sana ada Phupa.
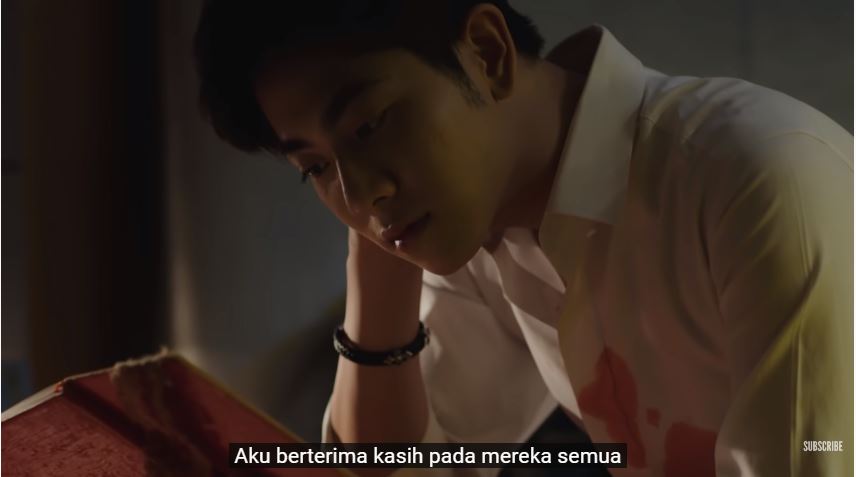
Dari adegan Tian membaca diari Torfun di episode 1, aku sebenernya mulai agak khawatir, karena isi diarinya adalah soal pengalaman Torfun yang menyenangkan di desa. Sebagai orang yang tinggal dekat dengan pedesaan dan pernah nyicip tinggal di ibu kota, dalam hati diem-diem aku menyangkal semua yang Torfun tulis (karena hidup di Jakarta tuh enak banget gak boong). Meski kemudian aku ingat soal latar belakang keluarga Torfun yang bisa bikin dia betah di desa (dengan ada atau tidaknya sosok Phupa); dia cuma tinggal sama bibinya yang judes naudzubillah, jadi ya jelas dia bakal lebih nganggap desa itu kayak rumahnya.
Selain itu, adegan baca diari ini adalah puncak dari kemelut (yailah) dari benak Tian semenjak dia tahu kalau dia gak jadi meninggal. Jadi mari kita bahas kembali episode 1.
Oke, pertama, kenapa Tian bisa ngide banget pergi ke Pha Pun Dao, desa terpencil di perbatasan bagian utara Thailand? Padahal dia orang kaya, ibunya ngemanjain, ayahnya pejabat, dan baru lima bulan selesai operasi transplantasi jantung?
Banyak yang bilang episode 1 itu ngebosenin, bahkan sampai ada yang gak lanjut nonton gara-gara episode satunya. Bisa dimengerti kalau penonton pengen nyari alur yang cepet dan momen manis tokoh utama; karena di episode ini, emang gak ada. Tapi episode satu punya banyak hal yang secara sinematis bikin aku kagum, dan justru mutusin buat nonton ATOTS sampai selesai selain delapan menit awal yang aku ceritain di tulisan sebelumnya.
Balik lagi ke pertanyaan di atas, kenapa Tian kepikiran buat jadi guru relawan? Perjalanan dia buat memutuskan ini tuh panjang banget. Kebayang sih kalau di novel bakal ngabisin satu atau dua bab. Kalau di series, semua dimulai dari saat dia bangun sehabis operasi.

Dia bangun dengan obrolan orang tuanya soal ini:

Jadi di malam Torfun meninggal, sebenernya jantung dia bukan untuk didonorkan pada Tian. Tian berhasil mendapatkan jantung karena orang tuanya ngasih uang ke Direktur Wanchai biar bisa nyalip antrian. Terus pas jalan-jalan keluar ruangan, dia kemudian denger perawat pada ngegosipin dia.
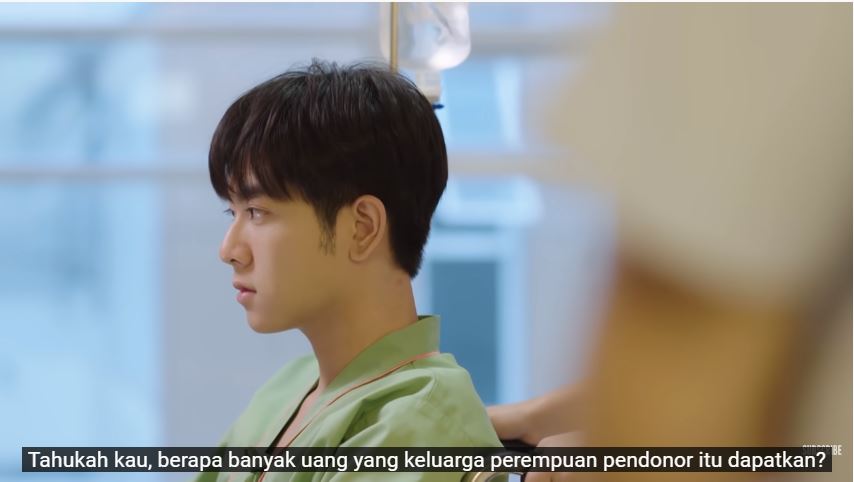
Inilah yang jadi awal mula kenapa ada perasaan bersalah dalam diri Tian, sekaligus kemarahan sama orang tuanya. Dia jadi selalu ngerasa ‘dihantui’ sama Torfun yang sosoknya pernah dia lihat dalam mimpi. Apalagi kemudian orang bilang itu keajaiban, terus temen-temennya ngomporin, gimana rasanya punya jantung orang lain? Karena secara gak langsung itu tuh kayak ngingetin Tian sama sesuatu yang seharusnya gak dia terima.

Karena misalnya aku tiba-tiba dapet duit nih, padahal aku tahu duit itu sebenernya hak tetanggaku yang miskin, cuma aku gak bisa balikin atau kasihin ke yang lain. Kalau ada yang nanyain gimana rasanya dapet duit itu, aku gak bakal bisa sepenuhnya jawab seneng. Malah sebel karena seolah-olah bikin aku jadi orang jahat (analoginya gak banget tapi ya semoga dimengerti, wkwk).
Hal itu yang kemudian bikin Tian kepo tentang Torfun, guru relawan di desa Pha Pun Dao yang bisa ia ketahui kehidupannya dari diari yang ia temukan. Sebelum Tian baca buku itu, ada satu adegan yang aku sukaaaaa banget.
Jadi ceritanya, Tian lagi ikut pertemuan dengan rekan-rekan orang tuanya. Di sini dia ketemu orang yang berjasa bikin dia bisa nyalip antrian untuk dapat pendonor.

Tahu apa yang nyebelin? Ini gak cuma soal orang dalam dan relasi, tapi berubah jadi soal bisnis. Si Bapak Wanchai ini minta imbalan, karena Ayah Tian itu ceritanya mantan sekertaris di Kementerian Kehutanan, dia pengen dibantu buat pembukaan lahan kosong karena anaknya pengen bangun hotel. Bah!
Ayah Tian iya-iya aja dong, tapi keadaan jadi gak enak saat si bapak tiba-tiba bilang gini.


Tian yang kesel langsung pamit buat ke toilet. Tapi baru balik badan, dia tiba-tiba ketabrak sama pelayan yang bawa wine.

Please, perhatiin di mana noda merah ngewarnain kemeja Tian. Pas nonton ini aku takjub sih, karena nodanya ada di dada sebelah kiri, tempat jantung :’
Tapi yang lebih bikin takjub lagi, ada adegan setelah ini. Dengan wajah yang bener-bener udah rarungsing karena permintaan maaf pelayan sama kekhawatiran ibunya, Tian akhirnya pamit buat bersihin baju. Tapi sebelum bener-bener keluar, dia balik badan dan kamera nunjukin ini.

Apa yang kalian lihat?
Dengan cuma kepisah sama dinding kayu, ada dua hal yang berbanding terbalik. Di sebelah kanan adalah orang-orang yang masih membicarakan pembebasan lahan (20 hektar btw) dengan santuy dan bahagia, dan di sebelah kiri ada seorang pelayan yang lagi dimarahin sama bosnya cuma karena kesalahan numpahin wine. *standingapplause* Scene singkat ini powerful banget menurutku, dia berhasil bercerita sesuatu yang kalau ada dalam tulisan bisa jadi satu paragraf panjang.
Nah, habis pulang dari sinilah Tian baca buku diari Torfun, sambil sesekali megangin luka bekas operasinya dibalik kemeja yang memerah.

Rangkaian adegan sebelumnya, bikin adegan baca buku diari ini kerasa kuat banget. Gimana kemudian Tian jadi ngebandingin hidupnya dan Torfun. Karena setelah divonis hidupnya gak lama lagi, Tian cenderung gak peduli lagi sama masa depan dan cuma bersenang-senang. Tokh gue bentar lagi mati. Sedangkan di buku, Torfun cerita tentang hidupnya yang jadi bermakna setelah mengabdikan diri buat ngajar anak-anak pedesaan. Dia juga jadi ngebandingin kamarnya yang serba nyaman, sama cerita Torfun soal kasur tipisnya yang udah keras. Adegan inilah yang ngebuat Tian akhirnya memutuskan buat pergi ke Pha Pun Dao, desa tempat Torfun mengajar. Gak peduli kalau sebenernya dia tuh kabur, dan gak minta izin dulu.

Oke, hidupku emang gak senyaman Tian. Tapi jujur lihat montase ini aku jadi ikut mikir, hidupku selama ini dipakai apa aja ya? Udah berguna belum ya bagi banyak orang? Kalau aku ada di posisi Torfun yang mati muda, apa ya yang bakal dikenang orang-orang soal aku? Dengan sekian fasilitas dan kenyamanan yang aku punya, aku udah ngelakuin apa aja? Walaupun aku gak divonis hidup bentar lagi kayak dokter, jangan-jangan aku sebenarnya terlalu egois dan gak peka sama sekitar.
Dalem banget.
Fiuh, aku jadi capek dan bakal ngelanjutin resensi di bagian selanjutnya aja, hahaha. Aku gak nyangka bakal sepanjang ini. Dah!
Oh ya, buat yang suka tulisanku dan pengen ngedukung buat tetep menulis, boleh banget ngasih tip atau langganan lewat karya karsa. Pembayarannya bisa lewat OVO, Gopay, ATM dsb. Link-nya ada di sini. Terima kasih!


